Penulis: Dhani Pelupessy
Pada suatu kesempatan, saya sempat mengikuti kegiatan bedah film berjudul “Merawat Air” yang diinisiasi oleh PolGov (Research Center for Politics and Government), Universitas Gadjah Mada. Saya menghadiri pemutaran film tersebut karena diundang oleh seorang teman yang juga merupakan anggota tim peneliti PolGov UGM. Film ini dibuat berdasarkan hasil penelitian PolGov bersama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai di Yogyakarta. Film tersebut sangat menarik karena menampilkan upaya masyarakat setempat dalam merawat air, khususnya sungai. Yang menarik bagi saya ialah upaya masyarakat dalam merawat air itu sering kali dilakukan dengan cara menjaga hubungan harmonis mereka dengan sesuatu yang dianggap mistis, yakni makhluk astral atau makhluk gaib—dalam istilah akademis disebut sebagai non-human yang non-material. Ada keyakinan yang hidup di masyarakat bahwa setiap tempat memiliki “penunggu”-nya, sehingga perlu dihormati keberadaannya. Salah satu bentuk penghormatan tersebut diwujudkan dengan merawat dan menjaga keasrian tempat-tempat yang diyakini dihuni oleh makhluk gaib tersebut. Di sinilah letak poin yang menurut saya sangat menarik untuk dicermati. Dalam tulisan ini, saya akan coba menggunakan perspektif tersebut untuk menelaah bagaimana masyarakat Siri-Sori Islam menjaga dan merawat alam di sekitarnya.
Jika kita cermati ulasan di atas, tampak bahwa dalam masyarakat modern yang cara berpikirnya rasional, ternyata juga masih tumbuh subur pemikiran tradisional yang sarat dengan unsur mistik di masyarakat. Sayangnya, ketika fenomena semacam ini muncul di masyarakat, tak jarang sebagian ilmuwan atau pengamat justru melabelinya sebagai bentuk pemikiran yang primitif, kuno, kampungan, atau ketinggalan zaman. Cara pandang yang cenderung menilai kepercayaan terhadap hal-hal mistik sebagai sesuatu yang irasional dan terbelakang telah menjadi bahan perdebatan yang panjang di ruang-ruang akademik. Namun, dalam tulisan ini saya tidak akan mengulasnya secara mendalam. Bukan karena persoalan ini tidak penting, tetapi karena saya ingin menjaga agar tulisan ini tetap mudah dipahami oleh siapa saja—terutama oleh para pembaca dari beragam latar belakang.
Sebetulnya, pemikiran masyarakat yang masih memegang teguh ajaran-ajaran mistik seperti keyakinan bahwa di setiap tempat ada penjaganya (makhluk astral) merupakan sebuah terobosan pemikiran yang patut diapresiasi. Masyarakat semacam ini, dalam konteks tertentu, bahkan dapat dijuluki sebagai citizen scientist, yakni warga yang mengembangkan pengetahuan dan kebijaksanaan lokal secara turun-temurun, sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, adalah sebuah tindakan yang mulia jika kita terus merawat dan menghargai cara berpikir masyarakat yang masih berpegang nilai-nilai mistik tersebut. Sebab di balik apa yang sering disebut sebagai “mistik”, sesungguhnya tersimpan suatu bentuk kearifan ekologis yakni upaya nyata untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup mereka, sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya di atas.
Di sebagian masyarakat Siri-Sori Islam saat ini, saya masih menemukan adanya keyakinan tradisional yang meyakini bahwa di lokasi-lokasi tertentu terdapat penunggunya. Sosok penunggu ini kerap disebut dengan istilah “orang tua-tua”. Ini adalah hal yang menarik dan, menurut saya, merupakan bagian dari kearifan lokal yang patut dipertahankan—tentu saja tanpa menegasikan keimanan kita dalam beragama. Namun, sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir, arus modernisasi tampak begitu kuat memengaruhi cara berpikir generasi muda di Siri-Sori Islam. Akibatnya, kepercayaan terhadap nilai-nilai mistik yang telah lama hidup di dalam masyarakat perlahan mulai memudar. Anak-anak muda yang merantau ke luar daerah untuk melanjutkan ke jenjang S1, ketika pulang ke kampung, sering kali membawa logika pembaruan ke tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini hampir kita temui di banyak desa di Maluku saat ini. Tujuan anak-anak muda itu sebenarnya mulia, yakni ingin membawa kemajuan bagi kampung halamannya. Namun, dampaknya tidak selalu tepat. Mengapa demikian?

Jawaban saya begini. Meminjam konsep David Harvey, ada enam momentum perubahan (six moments) yang membentuk dinamika masyarakat. Salah satu dari enam momentum tersebut adalah pengetahuan—dalam hal ini dapat dipahami sebagai pendidikan—yang diperkenalkan ke dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak muda yang sedang atau baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi, ketika kembali ke kampung, cenderung membawa serta pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka peroleh selama di perantauan. Pengetahuan ini, ketika diperkenalkan ke masyarakat, memang mampu mendorong terjadinya perubahan yang signifikan, baik dari segi cara berpikir maupun cara menyikapi berbagai hal. Namun, sering kali pengetahuan baru tersebut cenderung mendiskreditkan cara berpikir mistik yang telah lama tumbuh subur di dalam masyarakat. Dengan narasi untuk melawan segala bentuk “tabu” dan “pamali”, mereka sering kali mengabaikan bahwa nilai-nilai tersebut justru berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dan kelestarian lingkungan. Akibatnya, perubahan yang dibawa oleh generasi muda ini malah menjadi semacam boomerang yang justru merusak tatanan sosial masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh nyata yang kini terlihat adalah meningkatnya jumlah sampah yang berserakan di sepanjang pesisir pantai—sesuatu yang dahulu sangat dijaga karena diyakini sebagai tempat yang dihuni oleh “orang tua-tua”.
Persoalan sampah yang muncul belakangan ini bukan semata-mata masalah kebiasaan, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih fundamental yakni pergeseran cara berpikir masyarakat dari pola pikir mistik ke logika modern. Logika modern ini pada dasarnya cenderung menolak hal-hal yang berbau mistik, termasuk keyakinan terhadap pamali dan tabu yang selama ini telah menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat. Dulu, lokasi-lokasi tertentu yang diyakini memiliki “penunggu” sangat dijaga dan dihormati. Masyarakat enggan melakukan tindakan sembarangan di tempat-tempat tersebut, termasuk membuang sampah, karena rasa takut dan hormat terhadap keberadaan makhluk gaib yang diyakini menghuni area itu. Kini, karena kita tidak lagi mempercayai hal-hal semacam itu, tempat-tempat yang dulu dianggap sakral pun tak lagi diperlakukan secara istimewa. Akibatnya, sampah bahkan kerap dibuang di area yang dulu dikenal sebagai wilayah pamali yakni tempat-tempat yang dulu dianggap tabu untuk dikotori. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana namun menyedihkan adalah kita telah kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai mistik, pamali, dan tabu yang dahulu berfungsi sebagai mekanisme sosial dan spiritual untuk menjaga keharmonisan kita dengan alam sekitar.
Saya masih sangat ingat dengan cerita beberapa orang tua di kampung. Mereka pernah berbagi kisah kepada saya tentang pengalaman mereka waktu masih remaja. Dulu, katanya, mereka sangat takut berjalan di sepanjang bibir pantai, dan lebih-lebih takut lagi yaitu melakukan tindakan yang bisa mencelakakan diri sendiri seperti membuang sampah sembarangan. Apa yang membuat mereka takut? Jawabannya sederhana, karena mereka masih meyakini hal-hal yang berbau mistik. Mereka percaya bahwa di lokasi-lokasi tertentu ada “orang tua-tua” yang menjaga tempat itu. “Katong seng boleh biking sabarang di tampa itu,” begitu kata mereka. Beginilah logika mistik bekerja di tengah-tengah masyarakat. Efek dari keyakinan tersebut bukan hanya soal rasa takut, tetapi menghasilkan tindakan nyata yakni lingkungan menjadi terjaga dan tetap asri. Ketakutan untuk membuang sampah sembarangan berakar dari rasa hormat terhadap sesuatu yang tak terlihat, tapi diyakini hadir dan menjaga ruang-ruang tertentu. Dengan demikian, memelihara keyakinan terhadap nilai-nilai mistik sebenarnya juga berarti memelihara alam di Siri-Sori Islam. Ini bukan sekadar persoalan teknis tentang pengelolaan sampah, ini adalah persoalan yang sangat fundamental. Sebuah persoalan tentang cara pandang terhadap lingkungan, yang belakangan ini mulai tergeser, termasuk di berbagai desa di Maluku, dan khususnya di Siri-Sori Islam. ●














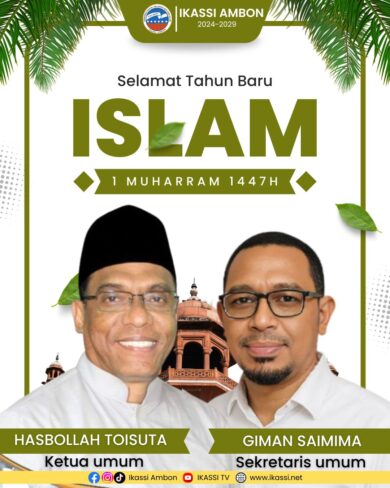



Discussion about this post